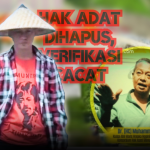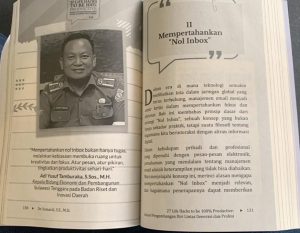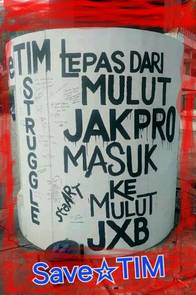CSR Konawe Gagal Melindungi Warga — Vonis Ini Menguak Paradigma Usang yang Mengakar
3 min read
CSR Konawe Gagal Melindungi Warga — Vonis Ini Menguak Paradigma Usang yang Mengakar
Opini oleh: Jumran, S.IP (Ketua Forum CSR Konawe)
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha beberapa bulan lalu yang menjatuhkan vonis bersalah kepada PLTU PT Obsidian Stainless Steel (OSS) atas pencemaran lingkungan menjadi titik balik penting dalam sejarah pengelolaan industri di Konawe. Putusan ini bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi sekaligus membuka secara telanjang kegagalan model tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selama ini berjalan di lingkar industri Konawe.
Selama bertahun-tahun, CSR di Konawe dipraktikkan dengan logika kewajiban: perusahaan memberikan bantuan karena dianggap harus memenuhi aturan, bukan karena masyarakat memiliki hak yang wajib dihormati. Logika kewajiban inilah yang membuat CSR terjebak sebagai ritual administratif—perusahaan merasa cukup dengan membagi paket bantuan, menggelar pelatihan seremonial, membangun fasilitas kecil, dan menyiapkan laporan rutin kepada pemerintah. Aktivitas ini tampak baik di atas kertas, tetapi tidak pernah menyentuh substansi perlindungan masyarakat maupun pemulihan lingkungan. CSR lebih sibuk menghasilkan dokumentasi daripada memastikan keamanan ruang hidup warga.
Putusan PN Unaaha mengungkap dampak dari paradigma keliru tersebut. Bagaimana mungkin perusahaan yang setiap tahun menampilkan kegiatan CSR secara besar-besaran tetap terbukti mencemari lingkungan masyarakat? Bagaimana mungkin program CSR tidak mencegah, tidak memperbaiki, bahkan tidak berhubungan dengan penderitaan warga akibat polusi udara, air yang tercemar, gangguan kesehatan, dan rusaknya ruang hidup?
Hal itu terjadi karena CSR berjalan di dunia paralel yang tidak terkait dengan dampak nyata di lapangan. Tidak ada baseline data sosial-ekologis yang dijadikan dasar, tidak ada pemantauan independen, tidak ada pengukuran risiko, tidak ada audit sosial, dan tidak ada mekanisme pemulihan yang terintegrasi. CSR hanya berfungsi sebagai penanda bahwa perusahaan telah “berbuat sesuatu”—bukan sebagai instrumen yang menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat. Ini adalah CSR yang sibuk pada tampilan, bukan pada tanggung jawab substantif.
Lebih jauh lagi, masyarakat hampir tidak memiliki posisi tawar dalam model CSR seperti ini. Dalam logika kewajiban, warga diposisikan sebagai penerima belas kasih. Mereka tidak memiliki mekanisme resmi untuk menuntut hak atas lingkungan bersih, kualitas air yang layak, atau pemulihan ekologis. Ketika warga mengeluh, keluhan itu kerap berhenti di meja birokrasi. Sementara itu, perusahaan dapat berlindung di balik laporan CSR tahunannya yang penuh dengan angka dan foto, tetapi kosong dari dampak perlindungan.
Paradigma keliru ini bukan hanya terjadi di Konawe. Di berbagai wilayah lain di Sulawesi Tenggara, pola yang sama terus berulang. Di perairan sekitar Teluk Moramo, perusahaan-perusahaan tambang menjalankan CSR berupa pelatihan UMKM dan program bantuan, tetapi air semakin keruh dan nelayan terus kehilangan ruang hidup. Di Kolaka, perusahaan nikel rutin melaksanakan program sosial, namun debu tambang tetap mencemari pemukiman dan mengganggu kesehatan warga. Di kawasan pesisir yang terdampak sedimentasi industri, CSR perusahaan sama sekali tidak diarahkan untuk memulihkan ekosistem, melainkan acara seremonial yang tidak relevan dengan penderitaan masyarakat.
Ini menunjukkan satu kesimpulan: CSR di Sulawesi Tenggara, termasuk di Konawe, lebih banyak berfungsi untuk menjaga citra perusahaan ketimbang melindungi warga dari risiko sosial-ekologis.
Karena itu, perubahan mendasar diperlukan. CSR harus meninggalkan logika kewajiban dan bergeser ke logika hak—sebuah pandangan bahwa masyarakat memiliki hak-hak mendasar yang tidak boleh dinegosiasikan. Hak untuk hidup di lingkungan bersih, hak atas air yang sehat, hak atas kesehatan, hak bebas dari pencemaran, hak atas ruang hidup yang aman, dan hak untuk dilibatkan dalam keputusan industri yang berdampak pada mereka. CSR berbasis hak menuntut perusahaan untuk mengidentifikasi dampak, mencegah risiko, memulihkan kerusakan, menyediakan akses keadilan, dan beroperasi secara transparan.
Tentu, perubahan paradigma ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan sadar tujuan—gerakan yang menuntut transparansi dokumen CSR, mendorong audit sosial setiap program perusahaan, memastikan CSR terkait langsung dengan pemulihan ekologis, memperkuat posisi tawar warga, dan memantau implementasi CSR di lapangan. Gerakan ini harus melibatkan masyarakat adat, organisasi petani dan nelayan, kelompok perempuan, akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis independen, hingga tokoh-tokoh lokal yang memahami konteks sosial-ekologis Konawe.
Putusan PN Unaaha adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah kesempatan berharga untuk mengubah arah tata kelola CSR di Konawe secara menyeluruh. CSR tidak boleh lagi menjadi acara tahunan yang dipenuhi dokumentasi foto tetapi kosong dari substansi. Tidak boleh ada lagi CSR yang memberikan bantuan seremonial tetapi tutup mata terhadap pencemaran yang mengancam hidup warga.
CSR harus menjadi alat keadilan sosial-ekologis yang benar-benar melindungi masyarakat. CSR harus memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di Konawe tidak hanya mengambil manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak dasar warga yang terdampak.
Dan yang paling penting: masyarakat tidak sedang meminta-minta bantuan—mereka sedang menuntut haknya untuk dilindungi. (*)