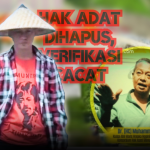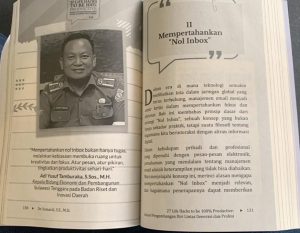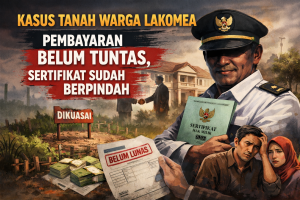Heroisme Digital dan Revolusi Naratif: Pembelajaran dari Fenomena Agam Rinjani
4 min read
Oplus_0
Heroisme Digital dan Revolusi Naratif: Pembelajaran dari Fenomena Agam Rinjani
Opini oleh : Dr Alem Febri Sonni MSi, dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin
KETIKA Abdul Haris Agam yang dikenal sebagai Agam Rinjani mendokumentasikan proses evakuasi wisatawan Brasil Juliana Marins dari jurang sedalam 600 meter di Gunung Rinjani, ia tidak hanya melakukan operasi penyelamatan.
Tanpa disadari, ia sedang menulis ulang grammar heroisme di era digital dan mendemonstrasikan bagaimana jurnalistik telah bertransformasi secara fundamental dalam lanskap media kontemporer.
Fenomena viral Agam Rinjani menawarkan laboratorium sempurna untuk memahami dinamika kompleks antara teknologi, narasi, dan konstruksi makna dalam masyarakat digital.
Dari perspektif antropologi media, kasus ini menunjukkan apa yang Henry Jenkins sebut sebagai “participatory culture,” di mana batas tradisional antara producer dan consumer informasi telah runtuh.
Agam, seorang pemandu lokal tanpa latar belakang jurnalistik, berhasil menciptakan narasi yang lebih powerful daripada coverage media mainstream karena ia memiliki dua elemen krusial: akses langsung dan autentisitas pengalaman.
Transformasi naratif yang terjadi dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui teori “moral panic” Stanley Cohen yang berevolusi menjadi “moral celebration.”
Pada fase awal, media sosial menciptakan konstruksi negatif terhadap tim SAR Indonesia.
Netizen Brasil yang frustration dengan lambatnya proses evakuasi mentargetkan kemarahan mereka kepada Agam dan sistem penyelamatan Indonesia.
Namun, ketika Agam mulai mendokumentasikan realitas operasional melalui video real-time, terjadi “narrative reversal” yang spektakuler pembalikan total konstruksi makna dari villain menjadi hero dalam hitungan hari.
Kunci dari transformasi ini terletak pada konsep “authenticity” dalam media digital.
Walter Benjamin dalam esainya tentang reproduksi mekanis menjelaskan hilangnya “aura” dalam karya seni yang direproduksi secara massal.
Paradoksnya, dalam konteks media sosial, “aura” justru dapat diciptakan kembali melalui dokumentasi real-time yang menghadirkan sense of immediacy dan intimacy.
Video Agam yang menunjukkan dirinya bermalam di tebing vertikal bersama jenazah Juliana menciptakan “authentic moment” yang tidak dapat direplikasi oleh jurnalisme konvensional dengan segala keterbatasan akses dan protokolnya.
Penggunaan teknologi Starlink untuk live streaming dari lokasi evakuasi menciptakan apa yang Guy Debord sebut sebagai “spectacle” realitas yang termediatisasi hingga batas antara kenyataan dan representasi menjadi kabur.
Namun, berbeda dengan kritik Debord terhadap society of spectacle yang alienating, spectacle yang diciptakan Agam justru menghasilkan empati dan understanding yang mendalam tentang kompleksitas operasi penyelamatan di medan ekstrem.
Dari perspektif jurnalistik digital, fenomena ini menggarisbawahi shifting paradigm dari “gatekeeping” menuju “gatewatching.” Axel Bruns menjelaskan bahwa dalam environment digital, fungsi journalist tidak lagi sekadar sebagai gatekeeper yang menyeleksi informasi, melainkan sebagai gatewatcher yang mengamati dan mengkurasi konten yang diproduksi oleh users.
Agam Rinjani, meskipun bukan jurnalis profesional, berhasil melakukan citizen journalism yang bahkan lebih impactful daripada coverage media tradisional karena proximity dan perspektif first-person yang tidak dapat ditandingi.
Benedict Anderson dalam “Imagined Communities” menjelaskan bagaimana media cetak menciptakan komunitas terbayang dalam konteks nation-building.
Dalam era digital, fenomena Agam Rinjani menunjukkan bagaimana media sosial mampu menciptakan “transnational imagined community” yang melampaui batas geografis dan cultural.
Netizen Brasil yang memberikan apresiasi kepada Agam menciptakan solidaritas virtual yang berbasis pada universal human values, bukan pada proximity geografis atau cultural similarity.
Yang menarik adalah bagaimana Agam menggunakan viral fame-nya bukan untuk personal gain, melainkan untuk advocacy.
Ia mengekspos kelemahan sistemik dalam infrastruktur keselamatan pendakian, tidak tersedianya shelter emergency, dan masalah kepemilikan alat rescue di kawasan Rinjani.
Ini mendemonstrasikan potential transformatif dari viral content sebagai instrumen social advocacy dan policy critique.
Pierre Bourdieu dalam “Distinction” memperkenalkan konsep “cultural capital” yang dalam konteks digital dapat dipahami sebagai kemampuan mengakumulasi social media capital melalui viral content.
Agam berhasil mengkonversi tragic event menjadi cultural capital yang membuatnya memperoleh 1,5 juta followers dalam hitungan hari.
Namun, conversion ini tidak terjadi melalui exploitation of tragedy, melainkan melalui authentic documentation of human courage dan professional dedication.
Michel Foucault dalam analisisnya tentang discourse menjelaskan bagaimana power dan knowledge saling terkait dalam construction of truth.
Dalam kasus Agam Rinjani, terjadi shifting discourse dari “institutional authority” menuju “experiential authority.
Kredibilitas tidak lagi ditentukan oleh institutional position atau professional credentials, melainkan oleh direct experience dan kemampuan mengkomunikasikan pengalaman tersebut secara authentic melalui platform digital.
Dari perspektif antropologi digital, fenomena ini juga menunjukkan transformasi ritual dan ceremony dalam masyarakat kontemporer.
Tindakan Agam bermalam di tebing bersama jenazah dapat dipahami sebagai modern ritual yang memiliki dimensi spiritual dan cultural significance, namun dikomunikasikan melalui digital medium untuk global audience.
Ini menciptakan hybrid form antara traditional ritual practice dengan contemporary digital storytelling.
Ketika tragic events menjadi raw material untuk viral content production, bagaimana kita dapat memastikan bahwa dignity of victims tetap terjaga?
Bagaimana kita dapat membedakan antara authentic documentation dengan performative heroism untuk social media consumption?
Fenomena Agam Rinjani pada akhirnya mendemonstrasikan bahwa dalam era digital, power to narrate telah democratically distributed.
Individual dengan access, authenticity, dan communication skills dapat menciptakan counter-narrative yang lebih powerful daripada institutional media.
Namun, dengan great power comes great responsibility.
Digital storytellers seperti Agam harus aware terhadap ethical implications dari viral content production dan menggunakan platform mereka untuk constructive purposes.
Pembelajaran utama dari fenomena ini adalah bahwa jurnalistik digital telah menciptakan new paradigm dalam construction of heroism, truth production, dan cross-cultural communication.
Media sosial bukan sekadar alat distribusi informasi, melainkan arena di mana makna dikonstruksi, identitas dibentuk, dan solidaritas lintas budaya diciptakan.
Dalam konteks Indonesia sebagai destinasi wisata global, fenomena Agam Rinjani menunjukkan potential media digital sebagai soft power instrument yang dapat mengubah persepsi international tentang professional competence dan humanitarian values bangsa Indonesia.
Ke depan, penting bagi praktisi media, policy makers, dan digital content creators untuk memahami dynamics ini dan menggunakannya secara responsible untuk nation-building dan cross-cultural understanding, bukan sekadar untuk viral fame atau commercial exploitation.(*)